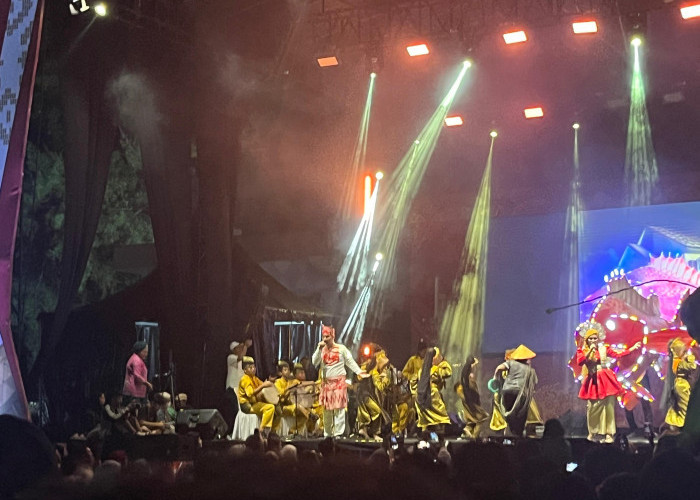Sempat Shock saat Sadari Anak Pertama Autis

Tri Gunadi, Terapis Anak Berkebutuhan Khusus yang Aktif Kampanye Red Flag
Peringatan Hari Anak 23 Juli besok diharapkan menjadi momentum penyadaran atas hak-hak anak berkebutuhan khusus, terutama autis. Tri Gunadi salah satu di antara sedikit terapis yang aktif mengampanyekan red flag perlunya penanganan sejak dini anak-anak ”istimewa” tersebut.
Laporan Dian Wahyudi, Jakarta
KAKI remaja 15 tahun itu dikunci belahan kayu yang menyatu dengan lantai rumah. Mirip fungsi pasung untuk membatasi ruang gerak seseorang yang dianggap membahayakan lingkungan sekitar. Akibatnya, remaja yang mulai beranjak dewasa tersebut hanya bisa duduk atau tiduran di lantai rumahnya yang sederhana.
Rumah itu hampir tak memiliki perabot. Meja dan kursi tamu saja tak ada, apalagi televisi. Sangat mungkin perabot di rumah itu telah dirusak oleh remaja tersebut. Sebab, saat kumat dan mengamuk, dia bisa membanting apa saja yang ada di sekitarnya.
Ayah remaja itu bekerja sebagai tukang ojek. Sedangkan ibunya menjadi buruh cuci. ”Kasihan. Dia sebenarnya salah satu anak autis yang terlambat tertangani karena kurangnya pemahaman keluarga,” ungkap terapis Tri Gunadi saat ditemui Jawa Pos di Klinik Tumbuh Kembang Anak Yamet, Cilandak, Jakarta, awal pekan lalu.
Kondisi keluarga itu makin memprihatinkan karena empat anak lainnya juga mengalami gangguan perkembangan mental seperti halnya si sulung. Mereka juga belum mendapatkan penanganan khusus sebagai pasien autisme. Setidaknya kondisi itu masih sama hingga sekitar enam bulan lalu, ketika Gunadi berkunjung ke rumah mereka di Dumai, Riau.
Di luar aktivitas mengajarnya di Program Okupasi Terapi Vokasi Universitas Indonesia, Gunadi juga aktif di banyak kegiatan yang berhubungan dengan gangguan tumbuh kembang anak. Bukan hanya di Yamet yang dirintisnya bersama istri, Anggita Yuliastuti, pria kelahiran Sukoharjo, 26 Mei 1976, itu juga terlibat di sejumlah lembaga lain yang masih berhubungan dengan penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama autis. Salah satunya, dia dipercaya untuk duduk sebagai pembina di Yayasan Cinta Harapan Indonesia (YCHI) yang menangani anak-anak autis tak mampu. Gunadi juga sering diminta untuk menjadi konsultan di beberapa institusi. Salah satunya adalah Pusat Inteligensia Kesehatan Kemenkes.
”Setahu saya, hingga saat ini belum ada data pasti jumlah anak autis di Indonesia. Tapi, banyak pihak, termasuk saya, yakin jumlahnya terus naik,” ucap dia.
Peningkatan jumlah penderita itu, papar Gunadi, potensial terjadi di daerah-daerah yang memiliki pusat-pusat industri dan pertambangan. Dumai yang dikenal sebagai kota minyak termasuk di antaranya.
”Jangan salah, di daerah-daerah itu cukup tinggi angkanya dan rata-rata belum tertangani dengan baik. Di Papua, misalnya, kecenderungannya juga terus meningkat. Kondisi ini sudah red flag,” kata dia.
Autisme pada anak memang tidak lepas dari faktor genetis. Namun, faktor keturunan itu tidak akan muncul kalau tidak ada pemicunya. Pencetus utamanya adalah kandungan logam berat beracun yang tinggi di dalam tubuh. Pemicu lainnya berupa virus, kuman, jamur, atau zat alergen.
Autisme sebenarnya sudah bisa dideteksi pada anak di bawah usia tiga tahun. Secara sederhana, deteksi bisa dilakukan lewat ajakan bermain cilukba. Jika anak belum bisa merespons ajakan bermain di usia tersebut, indikasi awal bahwa anak potensial autis sudah bisa ditangkap. ”Jadi, nggak mungkin anak empat tahun tiba-tiba autis,” jelas Gunadi.
Seperti halnya dengan deteksi yang bisa dilakukan sejak dini itu, penanganan untuk anak autis juga harus sejak dini. Sebab, jika tidak, gangguan perkembangan pada anak bisa melekat selamanya. Fisiknya bisa tetap tumbuh normal, tapi isi otaknya relatif kosong.
”Bahkan, jika tidak mendapat penanganan yang serius, autisme sangat berpeluang mengarah ke skizofrenia (gangguan jiwa, Red),” kata bapak tiga anak tersebut. Dia menyadari bahwa ada beban berat bagi orang tua ketika memiliki anak autis. Bukan hanya soal keterlibatan mereka dalam proses terapi si anak, tapi juga terkait dengan faktor eksternal. Yaitu, belum adanya pemahaman yang tepat tentang anak autis dari orang-orang sekitar.
Gunadi sadar betul situasi yang dihadapi para orang tua itu. Sebab, dia juga mengalaminya. Anak pertamanya, Enrico Verrelando (Verrel), 13, juga sempat menjalani terapi autisme.
”Saya yang tahu tentang autisme saja sempat shock saat mengetahui anak saya didiagnosis autis. Dunia seolah mau runtuh. Bayangkan bagaimana orang tua yang tidak tahu tentang kondisi anakya yang autis,” katanya.
Di keluarga besar pasangan Gunadi dan Anggita Yuliastuti, Verrel, yang lahir pada 2001, merupakan cucu pertama. Karena itu, wajar jika anggota keluarga lainnya menaruh harapan tinggi kepada buah hati pasangan yang menikah pada 2000 tersebut. Sejak sebelum menikah, keduanya memang terjun di bidang terapi anak-anak berkebutuhan khusus.
”Ini karena kamu atau istri kamu pasti membatin (punya anak autis) waktu hamil Verrel. Jadinya begini deh,” ungkap Gunadi, menirukan respons anggota keluarganya waktu itu.
Pernyataan yang setengah menyalahkan itu sempat membuat Gunadi dan istrinya makin drop. ”Saya lalu bilang kepada keluarga, ingin Verrel selamanya menjadi autis atau tidak. Kalau tidak, ayo kita sembuhkan bareng-bareng,” bebernya.
Verrel mulai menjalani terapi saat berusia 18 bulan. Tidak hanya dititipkan kepada terapis di Klinik Tumbuh Kembang Anak Yamet yang didirikannya bersama sang istri, Verrel juga diterapi sendiri oleh Gunadi. ”Bahkan, eyang-eyangnya juga ikut menerapi. Alhamdulillah, semua kooperatif,” tutur dia.
Memang dibutuhkan kesabaran ekstra untuk menanti progres hasil terapi pasien autisme. Hingga usia tiga tahun, Verrel belum bisa berbicara satu kata pun. ”Sekali lagi, saya yang tahu ilmunya saja juga sempat stres menghadapi situasi itu,” kenangnya.
Sampai-sampai dia ikut-ikutan melakukan tindakan yang tidak masuk akal secara keilmuan. Sebelum kembali berfokus pada tahap-tahap terapi dengan menyiapkan dan menyajikan 500 konsep kata, dia sempat mengikuti saran sejumlah orang. Yaitu, mengibas-ngibaskan lima lembar daun sirih yang ditanam di halaman rumahnya ke lidah Verrel tiap Jumat sepulang kerja.
”Itu saking stresnya saya. Saya saja mengalami situasi seperti itu, apalagi orang awam yang nggak tahu apa-apa (soal terapi autisme). Akibatnya ya seperti kasus pemasungan anak autis yang saya temui di Dumai,” ucap dia.
Hasil ketekunan Gunadi dan keluarga akhirnya terlihat. Menginjak usia 3,5 tahun, Verrel bisa mengucapkan kata-kata. Karena obsesif dengan handphone, kata pertama yang keluar dari mulut Verrel adalah ”halo”.
”Wuaduh, sueneng-nya minta ampun ketika Verrel bisa mengucapkan kata-kata itu,” tuturnya.
Sulung di antara tiga bersaudara itu menjalani terapi di klinik Yamet hingga umur lima tahun. Hasilnya, Verrel kini tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Dia saat ini duduk di kelas V SD. Hanya ketika sedang cemas atau grogi, Verrel terkadang masih kumat. Tangannya bergerak-gerak sendiri.
”Tapi, orang awam tetap akan sulit mengetahuinya,” jelas Gunadi sambil menunjukkan dengan bangga video Verrel bermain organ bersama grup musik sekolahnya dalam sebuah pentas beberapa minggu lalu.
Berkaca pada kondisi Verrel hari ini, penulis buku Mereka pun Bisa Sukses itu mengajak para orang tua anak autis untuk tetap bersemangat dalam menangani buah hati. ”Red flag harus tetap dikibarkan karena anak-anak (autis) juga anak bangsa yang merupakan bagian masa depan bangsa ini,” tegas dia.
Dua adik Verrel; Cattleya Verrenesa (Verren), 10, dan Carissa Verrinasya (Verrin), 4; tumbuh normal. ”Keberadaan Verrel membuat adik-adiknya makin nice perkembangannya. Saya terapkan pola asuh, asih, dan asah terhadap mereka seperti halnya yang saya lakukan kepada Verrel. Dia yang berjasa,” pungkas Gunadi. (*/c11/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: